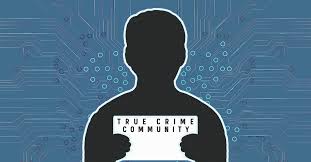Beberapa hari terakhir, publik kembali dikejutkan dengan penangkapan sejumlah terduga teroris oleh Densus 88. Pada 18 Juli 2025, aparat mengamankan seorang pria berinisial YK di Rumpin, Bogor. Sehari sebelumnya, tepatnya tanggal 17 Juli Densus juga menangkap LA, terduga teroris lainnya, di Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tahun lalu, sepuluh orang dengan dugaan keterkaitan jaringan terorisme juga ditangkap di wilayah Solo Raya.
Menariknya, dari luar, mereka tampak sebagai masyarakat biasa, bekerja dan berinteraksi seperti umumnya warga lain. Namun di balik keseharian itu, mereka ternyata bagian dari jaringan bawah tanah yang berpotensi melakukan serangan kapan saja. Ini menunjukkan bahwa meski serangan terbuka relatif jarang terjadi, sel-sel tidur dan proses rekruitmen kelompok teror masih aktif dan hidup di tengah masyarakat kita.
Fenomena ini menegaskan bahwa ancaman terorisme belum sepenuhnya hilang. Perekrutan, indoktrinasi, dan propaganda yang masif di media sosial tetap menjadi alat utama jaringan ini untuk memperluas pengaruhnya. Terorisme bukan hanya persoalan kekerasan fisik, tapi juga ideologi yang mengakar dan sulit dicabut.
Terorisme: Sejarah Panjang dan Dendam yang Dalam
Dalam sejarah manusia, praktik terorisme sudah berlangsung sejak era klasik. Meski bentuk dan tujuannya berbeda-beda, benang merahnya tetap sama: kekerasan sebagai alat untuk menciptakan ketakutan, mengacaukan stabilitas, atau mengekspresikan dendam dan ideologi.
Sayangnya, stigma negatif terhadap dunia Islam sebagai “produsen terorisme” masih kuat, terutama karena banyak negara muslim menjadi korban sekaligus lokasi utama konflik dan gerakan ekstrem. Kondisi ini semakin rumit dengan adanya kelompok-kelompok puritan yang memanipulasi ajaran agama untuk membenarkan kekerasan.
Di Mesir misalnya pada tahun 90an seringkali terjadi serangan teroris terhadap individu atau tokoh yang dianggap vocal menentang ajaran radikal, termasuk para pejabat tinggi negara pemangku kebijakan. Faraj Faoda misalnya yang menulis buku tentang Alhaqiqa Alghaiba sebagai respon atas buku yang ditulis oleh seorang ideolog radikal Abdul Salam Farah dengan judul Alfaridha Alghaiba di tembak di depan rumahnya saat ia sedang menuju mobilnya. Seorang jusnalis di Sudan pada tahun 2000n juga disembelih setelah diambil dari rumahnya hanya karena mengkritik ajaran radikal.
Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa setelah melakukan serangan, pelaku teror kerap “menghilang” seolah tidak lagi eksis. Tapi ketika situasi mulai lengah, mereka muncul kembali. Serangan pun dilakukan secara strategis dan sistematis, menyasar individu maupun instalasi penting yang sebelumnya telah diidentifikasi.
Kondisi ini membuat upaya penanggulangan terorisme tidak boleh berhenti meski tidak ada serangan. Istilah “zero attack” harus disikapi secara bijak. Nol serangan bukan berarti nol ancaman. Seperti api dalam sekam, jaringan-jaringan ini tetap bergerak di bawah tanah, membangun kekuatan sambil menunggu momentum yang tepat.
Doktrin dan Dendam sebagai Bahan Bakar Kekerasan
Salah satu penyebab mengapa jaringan terorisme sulit ditumpas adalah karena mereka digerakkan oleh doktrin yang kuat dan rasa dendam yang mendalam. Kebencian terhadap pihak yang berbeda pandangan menjadi bahan bakar ideologis yang menggerakkan tindakan ekstrem mereka.
Setiap serangan, dalam narasi mereka, adalah bentuk “pembalasan”. Hampir semua serangan-serangan terbuka yang dilakukan oleh kelompok terorisme dilatarbelakangi oleh dendam sebagai pembalasan. Contohnya, serangan 9/11 di Amerika Serikat diklaim sebagai respons terhadap kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Begitu pula sejumlah aksi teror di Indonesia dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas penangkapan rekan-rekan mereka, baik di dalam maupun luar negeri.
Dendam ini tidak pernah usang. Mereka menyimpan daftar nama dan lokasi target, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Mereka bergerak secara tak kasat mata, tapi sangat terorganisir. Dan ketika muncul, kerusakan yang ditimbulkan bisa sangat besar.
Melepaskan Diri dari Ideologi Kekerasan
Salah satu tantangan terbesar dalam melawan terorisme adalah melepaskan individu dari doktrin yang sudah mengakar. Terorisme bukan sekadar masalah hukum dan keamanan, tapi juga masalah ideologis dan psikologis. Melepas paham radikal yang sudah ditanamkan bertahun-tahun, apalagi dibungkus dengan narasi jihad dan surga, bukan perkara mudah.
Analogi sederhananya: bagi seseorang yang sudah terbiasa mengenakan jilbab selama bertahun-tahun, melepasnya adalah keputusan besar yang sangat sulit. Apalagi jika yang dilepas adalah ideologi yang dianggap suci dan menyatu dengan identitas religius mereka.
Oleh karena itu, istilah “zero attack” tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari ancaman. Ini hanyalah jeda yang bisa saja menipu. Di balik ketenangan, bisa saja ada gerakan yang menyusun kekuatan. Kewaspadaan dan pendekatan yang komprehensif—baik dari sisi keamanan, pendidikan, keagamaan, dan sosial—tetap harus menjadi prioritas.
Selama kebencian masih dipelihara, selama doktrin kekerasan masih beredar bebas di ruang-ruang sunyi, dan selama ideologi tidak disandingkan dengan akal sehat dan nilai-nilai kemanusiaan, maka ancaman terorisme akan terus mengintai. Kita semua punya tanggung jawab untuk tidak hanya waspada, tapi juga membangun benteng sosial dan spiritual untuk mencegah ideologi kekerasan tumbuh subur di tengah kita.
Wallahu a’lam.
 Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah