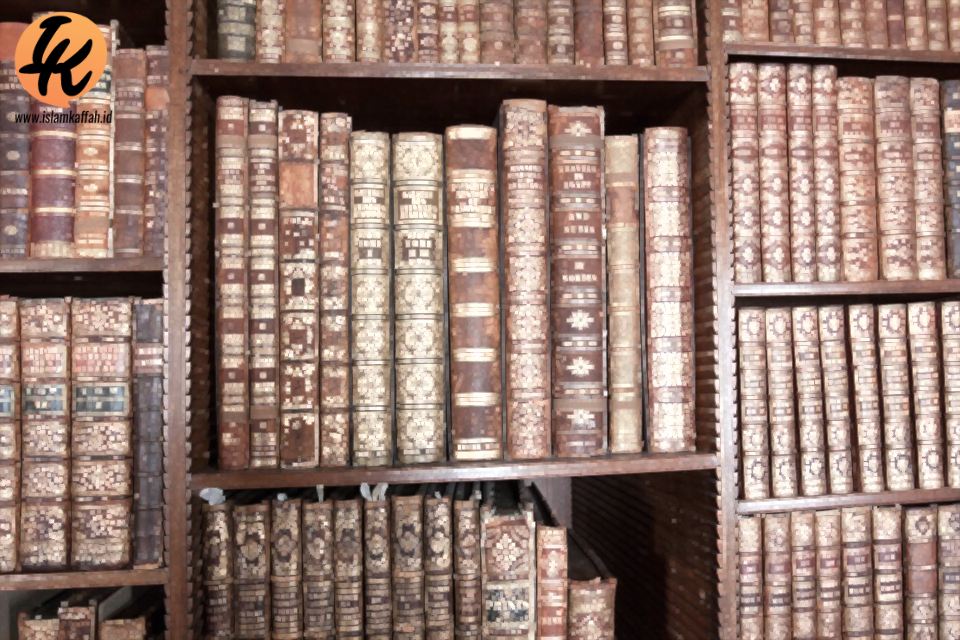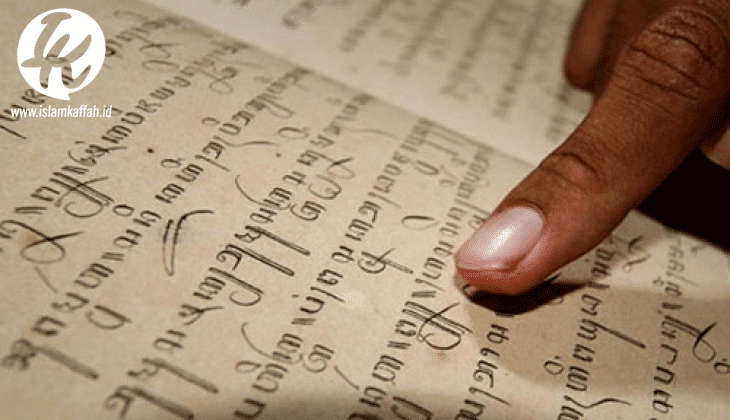Jargon back to Qur’an and Sunna sebenarnya bukanlah barang baru. Secara frontal ia sudah ada semenjak penghujung abad 18 dan semakin semarak hingga awal abad 19, dengan mengusung ideologi Muhammad bin Abdul Wahab (1703-92). Syaikh Zaini Dahlan dalam karyanya, al-Futuhat al-Islamiyya menuliskan bahwa gerakan yang dipelopori oleh Abdul Wahab tersebut merupakan keberlanjutan atas kegagalannya yang melarang banyak praktik keagamaan. Sampai pada tahun 1803 M invasi Wahabiyyah berhasil menyapu bersih Thaif dengan menguasai para Jemaah haji untuk tidak melakukan perbuatan yang menjurus pada khurafat seperti tawasul dan ziarah makam para wali.
Haraki semacam itu juga berpengaruh sampai ke Indonesia pada saat itu. Bahkan ada beberapa utusan dari Timur Tengah yang sengaja melaporkan kekejaman Wahabi tersebut kepada para ulama dan penguasa di Indonesia. Tetapi sebagian tokoh Indonesia justru ada yang mendukung gerakan Wahabiyyah tersebut, di antaranya para anggota Padri.
Laffan mencatat, sebagian mereka mengaku “orang-orang putihan” yang benar-benar taat terhadap ajaran agama. Sehingga melakukan aksi-aksi yang menonjol di Sumatera Barat saat itu, seperti melarang konsumsi alkohol, candu, bahkan melarang penajam gigi dan melarang sabung ayam.
Di Sumbawa juga demikian. Beberapa aksi puritanisme atau yang diklaim sebagai pemurnian agama dengan cara-cara yang radikal itu terjadi pada kisaran tahun 1815 di Gunug Tambora. Namun uniknya, para pemimpin mereka pada tahun 1845 masih dihormati oleh masyarakat sebagai wali. Ini cukup unik karena lepas dari domain Wahabiyyah yang sesungguhnya melarang keras adanya “perwalian.” Sama halnya dengan lukisan Pangeran Diponegoro yang membawa tasbih, itu juga menandakan adanya suatu perbedaan dari paradigma Wahabiyyah soal formalistik sebagai bid’ah.
Ini unik, mengingat jargon kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah diyakini sebagai pondasi Islam yang murni. Namun pada praktiknya tidak sepenuhnya murni seperti yang dipraktikkan di Arab sebagai rumusan tadisi besar (great tradition) Islam dalam tubuh Wahabiyyah. Meskipun sebenarnya tidak selalu demikian. Misalnya gerakan yang diinisiasi oleh Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.
Yudian Wahyudi dalam disertasinya membicarakan panjang lebar tentang problem ini. Tren kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah ternyata digunakan untuk melihat pemikiran-pemikiran progressif para ulama. Pada konteks Indonesia ia dominan melihat kontribusi Hasbi as-Sidiqi dan Nurcholis Madjid.
Menurutnya, dengan melihat pemahaman para intelektual yang menawarkan kontekstualisasi atau lebih disebut “pemikiran progressif” demikian cenderung menggunakan ayat Al-Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan. Namun masih tetap dalam kerangka bermazhab sebagaimana pedoman Ahlussunnah Waljama’ah.
Pedoman bermazhab di sini yang dipegang kuat-kuat oleh para ulama Indonesia, yang sampai sekarang masih dikembangkan menjadi basis pendidikan Pesantren dan madrasah. Azyumardi Azra dan Zamakhsyari Dhofier sepakat jika pesantren dan madrasah menjadi benteng Sunni dan melestarikan tradisi sanad. Sehingga keilmuan yang berkembang di pesantren memiliki output tidak radikal. Lalu, yang jadi problem apakah konsep kembali ke Al-Qur’an dan Sunnah atau gerakan dan pemikiran yang radikal?
 Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah