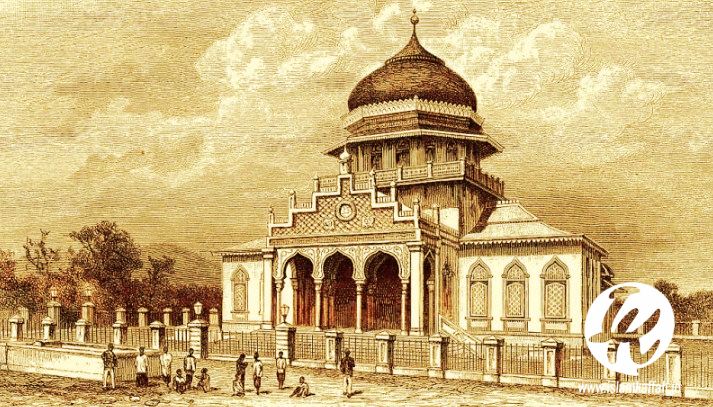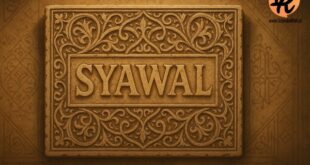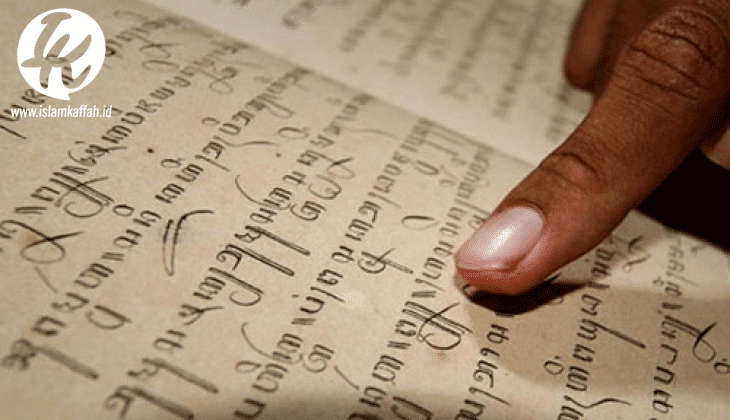Konsep menjadi manusia sejati sangat populer di kalangan kerajaan Islam masa lampau di Nusantara. Langkah ini dikenal dengan istilah martabat tujuh yang mengajarkan hubungan eksistensi Tuhan dengan makhluknya sehingga menghasilkan cerminan menjadi manusia sempurna.
Lelakon ini lazim dilakukan oleh orang-orang yang rindu dengan Tuhannya. Sehingga jika seorang hamba mampu meresapinya dengan benar, maka akan bertambah tajam penglihatan batinnya, semakin cinta kepada Tuhannya.
Sebenarnya, konsep itu merupakan pengembangan dari tajalli yang dikenalkan oleh sufi Andalusia, ibnu Arabi (1240 M) yang bisa kita baca dalam karya besarnya, Futuhat al-Makiyyah. Kemudian datang ke Nusantara dikembangkan oleh Burhanfuri dalam kitab Tuhfah al-Mursalah. Sehingga konsep ini pernah menjadi primadona para raja Islam seperti di Aceh.
Sebagaimana yang dikisahkan dalam Serat Centhini, buku sastra besar yang ditulis oleh para pujangga Jawa pada awal abad 19. Buku ini memuat beragam keilmuan yang diambil dari kisah-kisah para tokoh abad 17.
Dalam konteks pembahasan martabat tujuh, buku tersebut mengisahkan seorang Jayengresmi, putra dari Sunan Giri Prapen, saat memberikan pitutur kepada adik angkatnya yang bernama Rara Rukhanti sebelum menjadi istri sunan Cirebon, saat mengalami kegelisahan yang mendalam akibat ditinggal wafat oleh ayahnya, Syekh Trenggana.
Tuturnya dalam buku itu, martabat tujuh digunakan untuk mengenal Tuhan. Yaitu, martabat ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kemudian selanjutnya ada martabat Alam Arwah, Alam Mitsal, Alam Ajsam, dan yang ketujuh adalah martabat Insan Kamil (manusia sejati). Disebut pada bagian akhir, karena martabat ini merupakan tempat perkumpulan dari keenam martabat sebelumnya.
Tiga martabat pertama disebut kelompok batin. Sedangkan tiga berikutnya adalah martabat lahir. Kemudian menghasilkan insan kamil, artinya seseorang yang telah faham dan hatinya telah diliputi oleh kesadaran atas enam martabat sebelumnya sehingga menyadari keterikatan antara dirinya dengan Tuhannya yang tidak terpisahkan.
Di sisi lain, manusia juga disebut sebagai insan basyari, karena bersifat lahir dan batin. Dan tergolong sebagai jisim yang besar tipisnya berubah-rubah menurut unsur-unsur asalnya. Yaitu angin, tanah, air dan api. Keempat unsur itu yang menjadi karakter watak manusia. Dan sudah seharusnya menjadikannya sebagai cermin sehingga dapat mengenali adanya Allah. Supaya dapat mengendalikan empat unsur itu dengan baik, manusia dituntut bijak memberikan asupan kepada masing-masing unsur tersebut.
Untuk melengkapi pernyataan demikian, dalam kisah itu juga menyadur hadis Nabi yang mengatakan, “Siapa saja yang meliat segala sesuatu tetapi tidak menemukan adanya Allah di baliknya, maka tertipulah ia dengan penglihatan itu, dan sia-sialah penglihatan nya, dan tidak ada guna.” Menurutnya, orang yang demikian itu ibarat menyaksikan pertunjukan wayang, tetapi ia sama sekali tidak melihat adanya dalang, padahal nyata-nyata bahwa yang menggerakkan wayang dan yang bersuara itu adalah dalang.
Konsep ini sangat perlu dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menghadapi segala rintangan dan tantangan yang selalu bermunculan di muka bumi ini. Sehingga pada akhirnya akan menyadari bahwa semua itu perlu diterima sembari meningkatkan kualitas iman dan ihsan di sisi Allah.
 Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah
Islam Kaffah Media Pembelajaran Islam Secara Kaffah